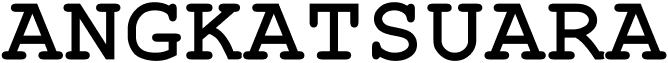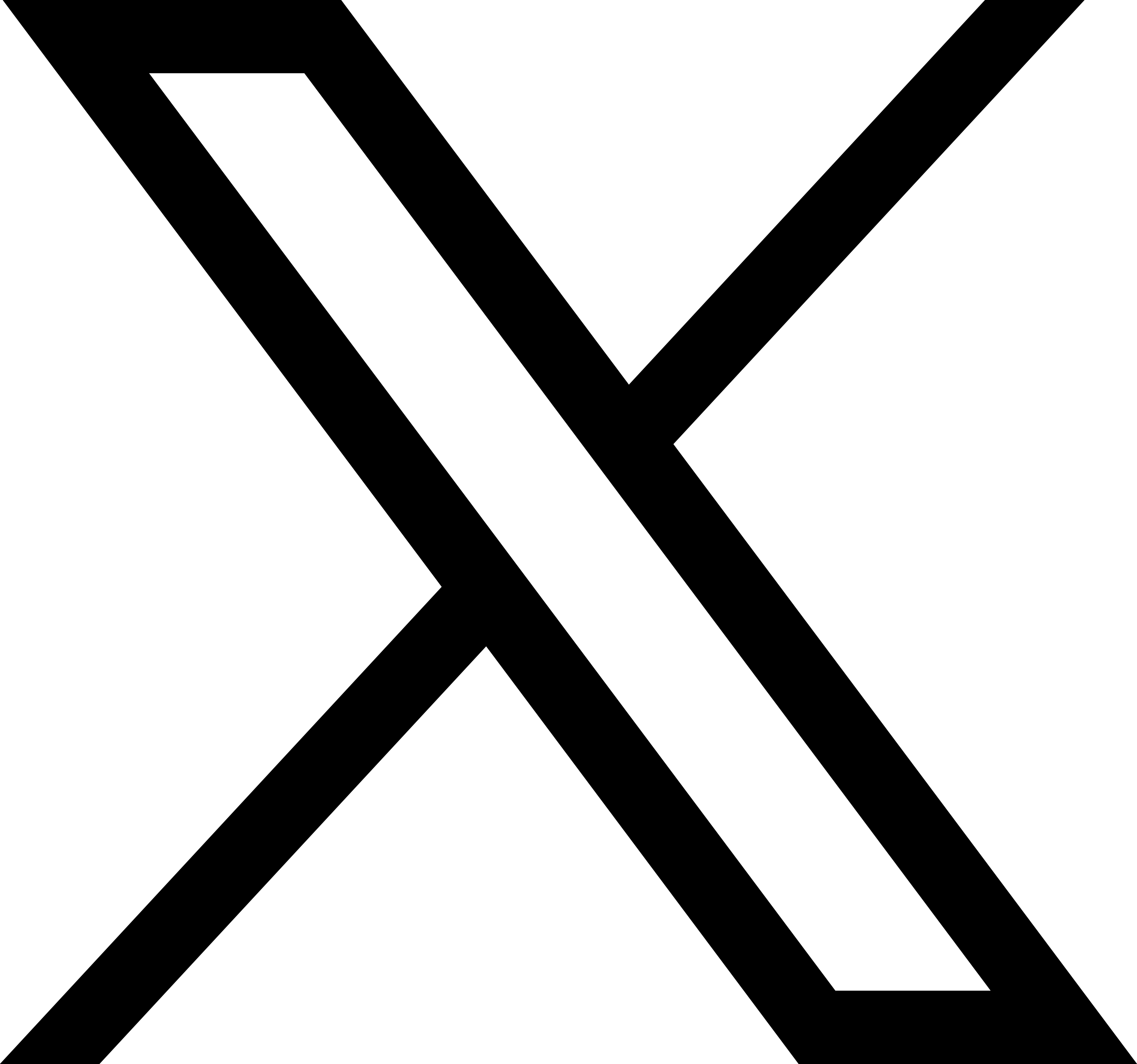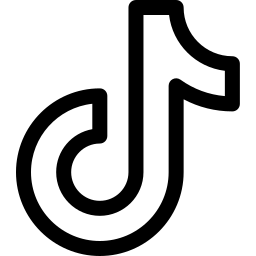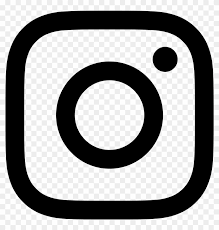“The bourgeoisie, wherever it has got the upper hand, has put an end to all feudal, patriarchal, idyllic relations.”
(Marx dan Engels dalam The Manifesto Communist)1
Beragam agenda perjuangan perempuan terus digaungkan oleh organisasi-organisasi perempuan saat ini. Dalam momentum politik, narasi dominan yang kerap dilantunkan oleh sebagian aktivis perempuan adalah “partisipasi perempuan dalam kontestasi elektoral”. Perempuan mesti menjadi pejabat publik, politisi, atau menduduki posisi strategis di birokrasi. Lebih-lebih, perempuan mesti merebut pucuk kekuasaan atau memegang kendali roda pemerintahan.
Laporan World Economic Forum bertajuk Global Gender Gap Report 2022 menunjukkan partisipasi perempuan di sektor politik terus mengalami tren peningkatan. Dalam jangka enam belas tahun, dari 2006 sampai 2022, persentase perempuan dalam posisi menteri nyaris meningkat dua kali lipat, dari 9,9% menjadi 16,1%. Di Parlemen juga menunjukkan tren serupa. Rata-rata global persentase perempuan di parlemen meningkat dari 14,9% menjadi 22,9%. Masih menurut World Economic Forum (2022), selama 50 tahun terakhir jumlah perempuan yang menjadi kepala negara dan menduduki pucuk pimpinan jabatan publik juga meningkat2.
Di Indonesia, posisi perempuan di wilayah strategis kekuasaan juga terlihat satu dekade terakhir. Dengan politik afirmasi 30%, perempuan seolah diberi ruang dan akses atas berbagai sumber daya politik. Kita tahu, pucuk pimpinan DPR saat ini adalah perempuan (meskipun keterwakilan perempuan di parlemen masih 20, 52% pada pemilu 2019), begitu pun di rumpun eksekutif tidak lepas dari kepemimpinan kaum perempuan. Sri Mulyani, Retno Marsudi, Siti Nurbaya, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, Tri Rismaharini dan Siti Nurbaya Bakar adalah representasi kaum perempuan di arena politik eksekutif. Keberadaan mereka seakan mengafirmasi pandangan bahwa perempuan telah diberikan ruang dan akses yang setara untuk menduduki posisi strategis kekuasaan.
Perjuangan yang Belum Selesai
Apakah dengan posisi strategis yang diduduki perempuan berarti perjuangannya telah berhasil? Apakah dengan eksistensi itu menandakan perempuan tidak lagi terperangkap dalam ruang domestik yang pengap, dapur yang gelap, lebih-lebih lepas dari hegemoni kultur patriarki?
Untuk menjawab aneka pertanyaan ini, saya lebih dulu mempertegas pemahaman saya tentang perempuan, bahwa perempuan bukanlah entitas yang homogen, tetapi mereka merupakan entitas yang terfragmen berdasarkan kelas-kelas sosial-ekonomi-politik tertentu. Dengan demikian, pemikir marxis perempuan, Rosa Luxemburg, sejak dulu memetakan agenda politik perempuan berdasarkan kelas sosial di dalam sistem kapitalisme. Alih-alih melihat perempuan sebagai identitas gender semata, Rosa memosisikan perjuangan perempuan di dalam kategori perjuangan kelas untuk menumpas kapitalisme. Artinya, perjuangan perempuan tidaklah netral, tetapi merepresentasikan strata kelas sosial tertentu. Sehingga nilai perjuangan yang dikumandangkan oleh perempuan borjuis berbeda dengan nilai perjuangan yang dimotori oleh perempuan proletar.
Perjuangan politik perempuan borjuis sejalan dan sebangun dengan agenda ekonomi-politik kapitalisme, yakni produksi komoditas. Rosa mengutarakan bahwa pembebasan perempuan dari sistem patriarki oleh kaum borjuis tidak dilandaskan pada kesadaran mereka atas hak-hak otentik kaum perempuan, namun sekadar diarahkan untuk memenuhi kepentingan kapitalisme dalam produksi komoditas. Perempuan dikerahkan untuk berkreasi di kantor-kantor, pabrik, bahkan di parlemen dan pucuk kekuasaan hanya untuk melanggengkan relasi produksi kapitalis, sehingga kehadiran mereka di ruang politik tidak mengubah apa-apa kecuali memposisikan dirinya sebagai agen dari segala kerusakan, ketimpangan, melanggengkan eksploitasi, singkatnya menopang sistem kapitalisme.
Hal demikian pula bisa dipotret dari dinamika keterlibatan perempuan di panggung politik Indonesia. Meskipun kaum perempuan telah menduduki posisi strategis di kekuasaan, namun mereka tidak memiliki power untuk mendesain kebijakan yang sensitif gender. Terbukti Undang-Undang Cipta Kerja, kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN), dan berbagai kebijakan oligarkis lainnya merampas ruang hidup kaum perempuan. Banyak dokumentasi menunjukkan bahwa kaum perempuan yang terdampak terjun langsung ke gelanggang perlawanan untuk mempertahankan ruang hidupnya dari pengkaplingan proyek kekuasaan.
Selain itu, anggaran publik yang berpijak pada pengalaman perempuan (gender based budgeting), belum sepenuhnya merasap ke berbagai bidang kecuali pada bidang-bidang yang identik dengan urusan perempuan4. Artinya, kedudukan perempuan di panggung politik kekuasaan tidak sepenuhnya dipandang sebagai keberhasilan perjuangan perempuan secara universal. Akan tetapi, itu hanyalah kemenangan para perempuan yang mempunyai privilege, kapital, atau koneksi dengan kepentingan oligarki.
Mungkin yang menjadi titik keberhasilan keterwakilan perempuan di kekuasaan saat ini adalah pengesahan UU TPKS. Tetapi hal ini tidaklah murni dari niat baik mereka yang berkuasa, melainkan bersumber dari perjuangan dan tekanan dari entitas perempuan ekstra parlementer. Dengan demikian, kita tidak bisa menitipkan harapan sepenuhnya pada perempuan-perempuan yang mendapat posisi istimewa di pangkuan kekuasaan. Akan tetapi, kepada mereka yang senantiasa bersolidaritas dan berjuang dari bawah, dari mereka yang termarjinalkan. Sebab, menurut Stephens & Stephens mereka adalah agen demokratisasi yang paling konsisten.
Daftar Pustaka
- Marx, K. & Engels, F. Manifesto of the Communist Party. (Marxists Internet Archive (marxists.org), 2005).
- World Economic Forum. Global Gender Gap Report. (2022).
- Mulyanto, D. Rosa Luxemburg: Sosialisme dan Demokrasi. (Marjin Kiri, 2019).
- Hasan, A. M., Anugrah, B. & Pratiwi, A. M. Gender-Responsive Budget Analysis on Social Protection Programs in Indonesia: A Case Study in Two Districts and A City. Jurnal Perempuan. 24, 27 (2019).
Sumber Gambar: Pinterest