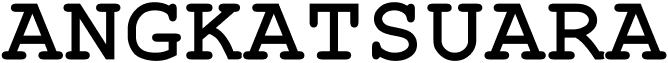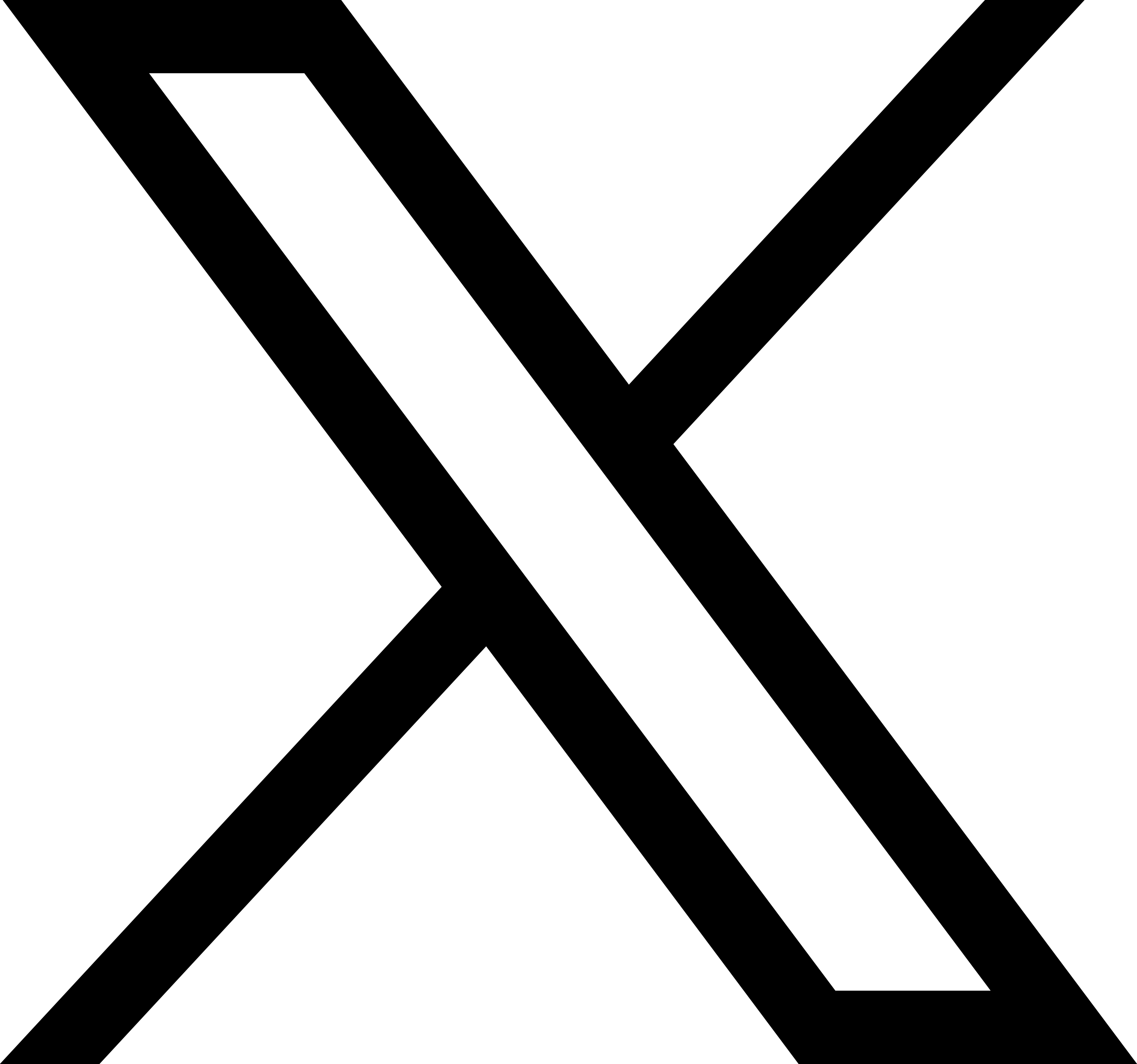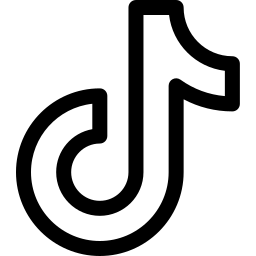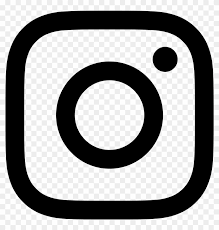Pemilu 2024 akan dilangsungkan sebentar lagi dan pemilu ini juga akan menjadi babak yang paling menentukan dalam menggambar sejarah Indonesia pada lima tahun ke depan. Tidak hanya soal arah bangsa Indonesia kedepannya di bawah kepemimpinan presiden baru, namun juga bagaimana kondisi sosial-politik yang akan ditempa setelah ini. Sebelumnya, sudah menjadi rahasia umum kalau kepemimpinan Jokowi selama dua periode mengalami dinamika yang luar biasa, dan bisa dikata kalau untuk sosial-politik, justru lebih menonjol regresinya dibandingkan dengan stagnasi.
Kasus seperti pelaporan Haris-Fathia, konflik agraria di Pakel, dan pembungkaman melalui UU ITE menjadi satu dari sekian bentuk regresi yang terjadi pada masa Jokowi. Kendati Jokowi selalu “menjual” pembangunan ekonomi sebagai warisan kekuasaannya, namun peningkatan ekonomi yang dialami Indonesia pada gilirannya tidak sebanding dengan perlindungan hak-hak sipil dan politik yang menjadi esensi dari demokratisasi di Indonesia, dan politik justru “seolah” diarahkan kepada mazhab integralisme yang menekankan stabilitas politik demi pembangunan ekonomi.
Alhasil, ekonomi yang bertumbuh justru menghasilkan ketimpangan keadilan yang besar bagi masyarakat karena buah dari pembangunan tersebut hanya dinikmati segelintir kelompok semata. Ketidakadilan tersebut masih terlihat hingga kini, baik itu rakyat miskin kota, masyarakat adat, dan bahkan kaum perempuan sekali pun. Salah satunya tertuju pada kasus Rempang yang viral akhir-akhir ini, di mana pulau yang berada di bawah yurisdiksi Pemerintah Kepulauan Riau menjadi sorotan usai upaya penggusuran ruang hidup masyarakat adat berlangsung.
Relokasi yang diniatkan untuk pembangunan Rempang Eco City kembali menuai pertentangan yang tajam antara hak masyarakat adat dengan kapitalisasi ruang yang digencarkan oleh aliansi bisnis-politik oligarki di Jakarta. Masyarakat adat yang sudah lama menghuni pulau tersebut dipaksa kehilangan ruang hidup hanya untuk investasi yang tidak ada manfaatnya bagi mereka dan sikap aparat yang cenderung memaksa penggusuran menjadi bukti bagaimana keterlibatan aparat hanya ditujukan untuk mengayomi kepentingan sepihak pemerintah.
Konflik Rempang menjadi satu dari sekian konflik agraria yang memarginalkan masyarakat adat yang memiliki hak untuk mengelola wilayah mereka sesuai dengan kearifan lokal di sana. Namun demikian, marjinalisasi masyarakat dalam konflik agraria tidak hanya berdampak pada suku-suku asli yang beranggotakan laki-laki, namun perempuan juga menjadi korban yang sering kali dipandang “sebelah” mata. Perempuan hingga masih menjadi pihak yang termarjinalkan dari dinamika sistem politik Indonesia selama dua dekade terakhir, di mana sistem patriarkal masih begitu kental dalam konteks relasi kuasa antara negara dengan masyarakat, bahkan konflik agraria sekali pun. Reformasi yang pada mulanya menjadi “asa” bagi perubahan sosial-politik bangsa Indonesia menuju demokrasi seutuhnya masih belum mencapai apa yang diharapkan, dan khususnya keadilan gender yang menjadi aspek terpenting dari demokrasi.
Pada konteks agraria, perempuan memiliki pengetahuan yang lebih besar dalam mengelola hasil bumi sebagaimana posisi mereka sebagai intelektual organik yang mampu mengubah lingkungan sekitar tanpa intervensi dari negara. Kelompok tani perempuan di Wadas dan beberapa wilayah lainnya menjadi bukti, bagaimana kerja sama antara peremuan dan laki-laki mampu menembus batas-batas patriarki dalam mengolah kekayaan alam mereka dan mereka saling berbagi peran untuk mencapai kesejahteraan mereka secara otonom.
Akan tetapi, dengan pola ekstraksi sumber daya alam yang berpusat pada negara untuk saat ini, pengelolaan wilayah pada akhirnya menjadi kapitalisasi sumber daya yang didukung oleh negara dan kekerasan juga menjadi metode untuk mengamankan praktik tersebut. Sebagaimana konflik di Wadas dan Rempang, penggusuran ruang hidup secara paksa oleh aparat tidak hanya memaksa petani pria kehilangan sumber pencahariannya, tapi juga kaum perempuan yang memiliki peran penting di dalamnya. Pembangunan Bendungan Bener dan Rempang Eco City secara langsung akan mengganggu keberlangsungan sarana pertanian dan perkebunan yang sudah lama ada.
Tidak hanya keberlangsungan sarana produksi masyarakat adat, pembangunan infrastruktur oleh pemerintah jelas memarjinalkan perempuan karena mereka akan kehilangan lingkungan sebagai identitas dan nasib mereka tidak akan lebih baik di hadapan rezim baru. Besar kemungkinan bahwa peran perempuan pasca-relokasi proyek investasi di Wadas hanya diletakkan pada peran-peran subordinat yang tidak lebih baik dari kelas pekerja dari proyek tersebut, seperti petani proletar hingga budak suruhan, dan hal ini jelas merendahkan martabat perempuan yang berhak mengelola hasil buminya sendiri.
Selain martabat, eksploitasi perempuan akan meningkat pesat ketika berhadapan dengan hal ini dan eksploitasi tenaga hingga seksual rawan menjadi hall umrah untuk mendukung akumulasi pada tahap selanjutnya. Dengan demikian, perjuangan politik tetap diperlukan diperlukan untuk mengembalikan kedaulatan perempuan di wilayah adat. Seperti yang terjadi di Wadas akhir-akhir ini, keberadaan gerakan Wadon Wadas menjadi komunitas yang mewadahi perjuangan kaum perempuan dalam melindungi wilayah mereka.
Tidak hanya menempatkan diri mereka di garis depan, komunitas ini juga melakukan pendidikan politik kepada warga Wadas akan pentingnya kedaulatan agraria, baik urun rembug, baca buku bersama, dan lain sebagainya. Dengan dua metode ini, maka perjuangan agraria sejatinya dapat dilakukan oleh kaum perempuan di seluruh Indonesia untuk meneguhkan posisinya sebagai manusia yang berdaulat. Tidak hanya berjuang secara sendiri, perjuangan bersama dengan kelompok kesatuan adat menjadi keharusan untuk mempertahankan hak-hak masyarakat adat yang saat ini semakin tergerus. Baik laki-laki maupun perempuan memiliki posisi yang setara dalam perjuangan dan dengan kekuatan masyarakat yang solid, maka kedaulatan bisa direbut kembali.
Sumber Gambar: Alinasi Masayarat Adat Nusantara