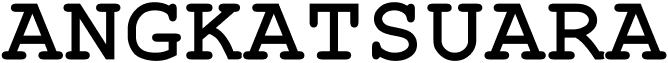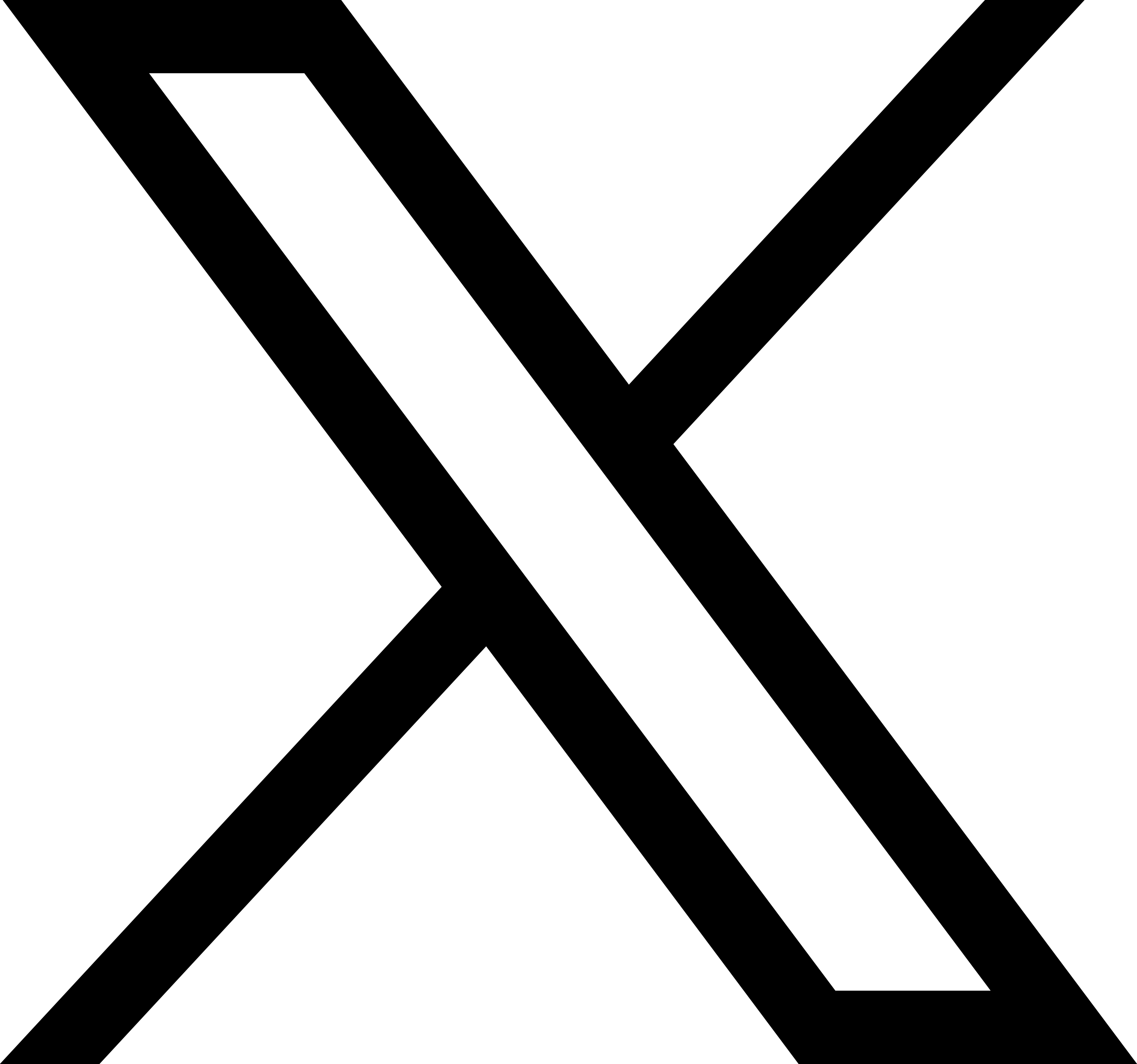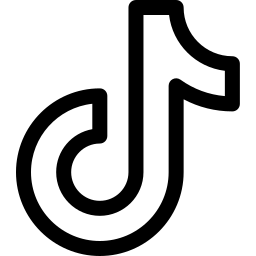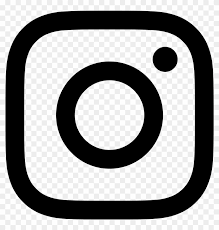Judul : Air dan Perempuan di Malang
Penyusun : Kolektif Women Ngalam Bergerak
Tahun Terbit : Juli – September 2024
Tebal : 68 Halaman
Hubungan perempuan dan alam merupakan sesuatu yang identik. Akan semakin jelas bila hubungan antara keduanya didudukkan dalam konteks yang lebih universal tentang bagaimana manusia mengelola alam. Pengelolaan yang cenderung hierarkis dan dominatif oleh manusia terhadap alam, pada akhirnya semakin menambah daftar ketidakadilan yang dialami oleh perempuan. Mengingat adanya keterkaitan simbolis antara alam dan perempuan yang sama-sama menjadi korban dari situasi tak adil akibat pola pembangunan yang mengadopsi nilai-nilai masyarakat patriarkis.
Meski bersifat tidak langsung, zine berjudul “Air dan Perempuan di Malang” (2024) yang dirilis oleh kolektif Women Ngalam Bergerak saya yakin, bertolak dari kesadaran serupa. Pada dasarnya, zine edisi kedua terbitan Women Ngalam Bergerak ini menjadikan persoalan tata kelola air sebagai pokok bahasan utama. Karena seperti yang ditulis pada tulisan pembuka berjudul “Melihat Bagaimana Air Bekerja”, hanya melalui air kita terus menerus dibimbing untuk menemukan jawaban atas berbagai persoalan yang dialami masyarakat, khususnya para perempuan di Kota Malang. Adapun yang dijadikan objek studi dalam hal ini adalah Sungai Brantas sebagai sungai terbesar kedua di Pulau Jawa setelah Bengawan Solo.
Pokok bahasan dalam zine dibagi ke dalam lima tulisan yang saling berhubungan. Selain esai, zine juga memuat serta catatan reportase hasil wawancara bersama penduduk lokal. Membacanya saya nyaris tidak menemukan kesan amatir yang selama ini lekat dengan citra zine sebagai media publikasi alternatif. Tetapi sebaliknya, yang saya jumpai justru kelima tulisan tersebut disusun secara ekstensif dan ditunjang oleh data yang cukup memadai.
Melihat Sungai Brantas dari Hulu ke Hilir
Zine mengawali pokok bahasannya dengan mengajukan esai kolaboratif berjudul “Sungai Brantas dari Titik Nol”. Adapun yang menjadi fokus utama tulisan tersebut adalah aspek kelola yang mencakup keseluruhan bagian Sungai Brantas. Dimulai dari bagian hulu yang berupa mata air yang ada di Kota Batu, hingga bagian hilir yang ada di Selat Madura.
Atas nama konservasi, negara lewat perantara Jasa Tirta I melindungi mata air Sumber Brantas dengan menjadikannya arboretum. Penetapan ini membuat segala kepentingan, baik eksploitasi air oleh korporasi, maupun pemanfaatan minimum oleh warga sekitar tidak diperbolehkan. Akan tetapi, sayangnya penetapan ini belum memayungi sejumlah mata air seperti Pesanggrahan I dan Pesanggrahan II yang kini keberadaannya terancam oleh eskalasi pembangunan demi kepentingan industri energi (geothermal), pariwisata, maupun pertanian. Hal tersebut memicu sejumlah ancaman seperti kelangkaan air, hingga bencana ekologis yang lebih mengerikan.
Kondisi tersebut semakin diperparah oleh kontrol negara atas aliran Sungai Brantas. Lewat proyek Brantas, negara mengontrol air Sungai Brantas menggunakan prinsip “One River, One Plan, One Integrated management”. Prinsip ini dikenal sebagai sebuah sistem pengelolaan terpusat yang dalam sejarah baru ditemukan pada era kolonialisme, tepatnya saat Belanda memberlakukan sistem tanam paksa (cultuurstelsel) demi mengisi kas ekonomi pemerintah kolonial. Satu kesamaan dari prinsip pengelolaan ini di era kolonial, maupun Indonesia modern terletak pada praktiknya yang sangat monopolistik dan cenderung mengalienasi masyarakat dari keberadaan sungai.
“Pada intinya, dari mata air Sumber Brantas hingga aliran sungai Brantas, semua dikontrol negara melalui proyek Brantas. Monopoli aliran sumber Brantas untuk konservasi, irigasi, dan penghalau banjir ini awalnya bertujuan untuk kesejahteraan warga. Tapi dalam prosesnya, proses kontrol air oleh negara ini tidak melibatkan masyarakat bahkan menghalau mereka untuk mendapatkan akses air untuk kebutuhan sehari-hari”. (hlm 12)
Praktik ini tentu sangat bertentangan dengan fakta perihal hubungan tak terpisahkan antara masyarakat dan Sungai Brantas. Untuk mendukung gambaran tersebut, pembahasan zine kemudian melompat ke tulisan kedua dari Doyan Dwi Dharma dengan judul “Menelusuri Sejarah Peradaban Sungai Brantas di Kota Malang”. Secara umum, tulisan kedua ini lebih banyak mengeksplorasi bukti-bukti historis yang mengerucut pada tesis utama penulis tentang peran vital Sungai Brantas bagi peradaban manusia yang ada di sekitar alirannya. Di mana dari bukti-bukti yang tersedia menunjukkan betapa Sungai Brantas adalah penopang utama peradaban manusia lintas zaman.
Ditemukannya fosil Homo Wajakensis oleh Van Rietschoten di lembah Sungai Brantas pada tahun 1889, menjadi salah satu bukti bahwa Sungai Brantas memainkan peranan penting sebagai penunjang kelangsungan hidup manusia di era pra-sejarah. Hal yang sama juga terjadi di era kerajaan klasik seperti era kerajaan Kanjuruhan, maupun Singhasari. Keberadaan situs petirtaan dan arca yang ditemukan di sekitaran wilayah Sungai Brantas menjadi bukti historis tentang bagaimana peradaban kerajaan klasik yang memandang penting keberadaan Sungai Brantas sebagai penopang utama peradaban manusia dari segi sosial, ekonomi, politik, maupun budaya. Bahkan pemilihan Tumampel sebagai ibu kota di era Kerajaan Singhasari pun tidak terlepas dari peran vital Sungai Brantas bagi peradaban yang eksis saat itu.
Peran inilah yang kelak, di kemudian hari turut dikembangkan oleh seorang arsitek asal Belanda kenamaan Thomas Karsten untuk mengatur tata ruang Kota Malang di era pemerintahan Hindia-Belanda. Karsten menyadari bahwa Kota Malang adalah kota yang sejuk dan karenanya untuk menjaga resapan suhu udara tetap stabil, ia memanfaatkan keberadaan Sungai Brantas. Setiap bangunan didesain menghadap ke arah sungai dengan harapan agar sungai ditempatkan sebagai taman kota dan mampu memberi manfaat yang lebih besar bagi warga Kota Malang. Sebuah gambaran yang sudah barang tentu bertolak belakang dengan perencanaan tata ruang Kota Malang pasca-kolonialisme.
“Sebagai masyarakat beradab, seharusnya kita dapat mencontoh bagaimana orang terdahulu memandang sungai. Sungai seharusnya menjadi teman. Tetapi hari ini sungai dianggap membawa bencana, entah itu banjir, longsor, juga dipenuhi dengan berita anak hanyut, tempat bunuh diri, dan itu sangat berseberangan dengan keindahan sungai yang dicita-citakan oleh para pendahulu.” (hlm 25)
Irisannya dengan Persoalan Perempuan Perkotaan
Dari pembahasan yang disajikan oleh dua tulisan pertama dalam zine, dapat diambil kesimpulan bahwa buruknya tata kelola yang monopolistik dan cenderung mengalienasikan masyarakat dari sungai sebagai sumber kehidupan mereka, sangat berdampak pada pemunggungan sungai oleh masyarakat. Segala hal yang menyangkut kelestarian sungai sudah tidak lagi dianggap penting karena kebutuhan akan air bersih yang sepenuhnya ditopang oleh sejauh mana kemampuan ekonomi warga. Terutama dalam hal membayar iuran bulanan dari PDAM, atau membayar listrik untuk memompa air dari dalam tanah. Celakanya karena tidak semua warga memiliki kemampuan ekonomi yang sama, sehingga degradasi lingkungan yang disebabkan oleh buruknya tata kelola yang monopolistik dan cenderung mengalienasikan masyarakat dari sungai dengan segera memunculkan masalah bagi masyarakat, terutama perempuan perkotaan.
Masalah tersebut dibahas secara khusus lewat esai kolaboratif berjudul “Masalah Atas Air adalah Masalah Perempuan di Perkotaan : Kajian Studi atas Sumber Mata Air Binangun”. Pembahasan dimulai dengan pertama-tama menyoroti kebutuhan perempuan atas air bersih. Di Kota Malang sendiri, kebutuhan ini banyak dibebankan pada Sumber Mata Air Binangun. Sumber mata air yang memiliki debit air 250 liter per-detik ini dimanfaatkan untuk mengairi beberapa kelurahan seperti Bandulan, Mergan, Sumbersari, Gajayana sampai beberapa kampus ternama yang ada di Kota Malang. Tata kelola atas Sumber Mata Air Binangun sepenuhnya dipegang oleh Perumda Air Minum Tirta Kota Malang dengan melibatkan warga sekitar sebatas pada aspek perawatannya saja.
Namun seperti yang telah disebutkan bahwa Sumber Mata Air Binangun sebatas difungsikan untuk memenuhi kebutuhan air di beberapa wilayah saja. Sementara itu, pesatnya perkembangan kota yang secara tidak langsung mendorong kemunculan pemukiman informal menimbulkan masalah baru terkait akses masyarakat terhadap air bersih. Pihak yang sangat dirugikan dalam hal ini lagi-lagi adalah perempuan perkotaan yang hidup di lapisan paling bawah piramida strata sosial. Sebab mereka memiliki opsi yang lebih terbatas dalam hal memilih dan memilah air yang akan mereka konsumsi di tengah degradasi lingkungan yang terus terjadi.
“Selain mata air, sungai pun mulai tercemar. Limbah produksi, limbah rumah tangga, bahkan limbah medis juga turut andil di dalamnya. Nahasnya, tidak sedikit warga yang tetap mengakses mata air maupun sungai tersebut karena tak ada lagi opsi lain.” (hlm 37)
Berada pada titik kerentanan semacam itu, perempuan perkotaan semakin dituntut untuk memiliki peran yang lebih besar dalam proses pengambilan kebijakan terkait air. Terlebih karena jika ditelusuri lebih jauh, kerentanan tersebut inheren dengan kenyataan tentang pembangunan dan kebijakan tata kelola air yang selama ini diberlakukan cenderung tidak melibatkan serta partisipasi masyarakat, khususnya kaum perempuan perkotaan. Terkait hal ini, zine menghadirkan dua catatan wawancara berjudul “Kisah Perempuan dalam Pusaran Perjuangan Mata Air Gemulo” dan “Ngugemi Tradisi : Potret Singkat Desa Giripurna dalam Menjaga Sumber Mata Air”. Berbeda dari tiga tulisan sebelumnya yang lebih mirip pengantar untuk memahami persoalan tata kelola air di Kota Malang, dua catatan wawancara tersebut lebih menyoroti perihal peran perempuan dalam perjuangan menuntut perbaikan tata kelola air berdasarkan pengalaman empiris mereka.
Pada catatan wawancara pertama berjudul “Kisah Perempuan dalam Pusaran Perjuangan Sumber Mata Air Gemulo”, pembaca lebih banyak dihadapkan pada penuturan cerita dari warga tentang perjuangan masyarakat Gemulo dalam rangka menyelamatkan mata air dari rencana pembangunan hotel yang disinyalir akan mengakibatkan krisis air dan kerusakan ekologis yang berkepanjangan. Lewat sebuah organisasi kenamaan Forum Masyarakat Peduli Mata Air (FMPMA, perjuangan warga mengadopsi model politik demokrasi langsung dengan memanfaatkan saluran formal lewat hiring bersama pemerintah setempat, hingga saluran informal dengan membuat pernyataan di muka umum atau demonstrasi. Selain memakan waktu, perjuangan yang dilakukan oleh warga tak sekali dua kali menemui jalan terjal. Namun hal tersebut bisa teratasi dengan baik lantaran kuatnya solidaritas di level akar rumput dan yang tak kalah penting ialah peran dukungan para perempuan yang tergabung dalam gerakan.
“Para ibu-ibu di kampung Cangar ini, sangat proaktif menunggu info dan perkembangan setiap kasus yang dihadapi. Ketika ibu-ibu ini berkumpul dalam forum perkumpulan arisan atau pengajian, mereka juga cenderung mendiskusikan kasus. Yang paling frontal dari dukungan perempuan Gemulo adalah, mereka bahkan berani menyuruh suaminya keluar dari tempat kerjanya hanya agar suami-suaminya bebas bergerak dalam gerakan”. (hlm 54)
Lain halnya dengan warga Gemulo yang berusaha memengaruhi kebijakan lewat gerakan politik, warga Desa Giripurna justru mengambil perjuangan kultural demi kelestarian sumber mata air. Karena seperti yang didokumentasikan oleh Lutfiana dan Mochammad Rizky lewat catatan yang berjudul “Ngugemi Tradisi : Potret Singkat Desa Giripurna dalam Menjaga Sumber Mata Air”, diketahui bahwa selain menerapkan pembersihan berkala serta melakukan penanaman pohon, warga Desa Giripurna juga menjaga mata air dengan cara merawat tradisi. Menarik karena dalam perjalanannya, tradisi yang ada di Desa Giripurna melibatkan serta peran perempuan untuk mengelola air. Setelah ditelusuri lebih lanjut oleh penulis, ternyata upaya pelibatan tersebut masih ada kaitannya dengan kepercayaan warga akan kedekatan hubungan antara perempuan dan air yang sepenuhnya filosofis.
“Simbol air itu diyakini sifatnya sebagai ibu, maksudnya seperti memberi kehidupan, terus dia lebih tenang. Jika ibu bisa jadi laki-laki, bisa jadi kepala rumah tangga, begitu pun dengan air”. (hlm 67)
Minim Abstraksi Teoritis dan Masih Bias Nilai
Pesatnya modernisasi dan pembangunan selama ini telah memunculkan persoalan-persoalan baru yang terkait dengan isu kelestarian lingkungan. Karena itu pada akhir abad ke-20, muncul gerakan di berbagai belahan dunia yang berfokus pada isu penyelamatan lingkungan. Dampaknya terhadap perkembangan ilmu sosial saat itu ditandai dengan munculnya berbagai paradigma baru yang lebih berwawasan lingkungan. Di lingkup internal gerakan perempuan sendiri muncul ekofeminisme sebagai salah satu cabang pemikiran feminis.
Dalam sejarahnya, awal kemunculan paradigma ekofeminisme didorong oleh kondisi faktual tentang beredarnya berbagai mitos yang berusaha mengasosiasikan alam dan perempuan. Misalnya seperti penggambaran bumi sebagai perempuan dan lain sebagainya. Mitos yang sarat dengan bahasa metafora ini dalam realitasnya di masyarakat patriarki terkadang menimbulkan penafsiran negatif ketimbang sebaliknya. Karena seperti halnya alam, terdapat kecenderungan dalam masyarakat patriarki untuk menjadikan perempuan sebagai objek yang dikuasai oleh kaum laki-laki.
Oleh sebab itu, berbicara tentang ekofeminis mutlak hukumnya untuk membicarakan ketidakadilan terhadap perempuan. Ketidakadilan dalam konteks ini pertama-tama harus dilihat sebagai akibat dominasi manusia terhadap non-manusia, atau alam. Dikarenakan alam selalu dikaitkan dengan perempuan, maka secara konseptual, simbolis dan linguistik terdapat korelasi antara isu ekologi dan lingkungan. Walau begitu, para pemikir ekofeminis sangat menghindari argumen yang mengasosiasikan alam dan perempuan berdasarkan mitos atau stereotipe yang men-subordinasi kaum perempuan. Akan tetapi lebih melihat hubungan tersebut sebagai titik tolak kesadaran feminis untuk mengupayakan kesetaraan relasi antara manusia dan non-manusia (alam), begitu pun dengan perempuan dan laki-laki.
Lantas apa hubungannya dengan totalitas pembahasan dalam zine? Pemilihan tema perihal air dan perempuan jelas tidak bisa dilepaskan dari pokok bahasan mengenai ekofeminis. Terlebih di beberapa bagian terdapat argumentasi yang mencoba mengasosiasikan tata kelola air di Kota Malang dengan pembangunan yang merepresentasikan nilai-nilai maskulin. Walau tidak didukung elaborasi yang cukup, argumen tersebut menjadikan pokok bahasan dalam zine tentu saja beririsan dengan persoalan yang umum disorot oleh para pemikir ekofeminis.
Pokok bahasan dalam zine memang telah cukup komprehensif dalam melihat hubungan tata kelola yang tidak adil terhadap alam dan hubungannya dengan ketidakadilan yang dialami kaum perempuan perkotaan. Namun minimnya abstraksi teoritis dalam hal ini membuat paparan yang ada terkesan masih sarat akan bias nilai patriarkis. Kecenderungan tersebut salah satunya dapat diamati dari beberapa tulisan yang memaknai ketidakadilan yang dialami perempuan akibat tata kelola air yang hierarkis dan dominatif terhadap alam. Di mana ketidakadilan dalam pemahaman para penulis masih didasarkan kepada peran perempuan di wilayah-wilayah domestik yang sepenuhnya merupakan hasil konstruksi sosial dalam masyarakat patriarki.
Selain itu, konsekuensi lain dari minimnya abstraksi teoretis dalam zine juga turut memengaruhi pemaknaan terhadap peran perempuan dalam wacana pengelolaan lingkungan, sebagaimana yang didokumentasikan lewat dua catatan reportase terakhir. Alih-alih diabstraksikan sebagai upaya yang lahir dari kesadaran perempuan akan pentingnya peran mereka dalam wacana pengelolaan lingkungan. Lewat wawancara yang secara proporsional lebih banyak dilakukan bersama narasumber laki-laki, cerita tentang peran perempuan dalam wacana pengelolaan lingkungan justru digambarkan hanya sebatas efek domino dari gerakan yang lebih dulu diinisiasi oleh warga. Terlebih lagi, penggambaran tersebut dibumbui pula dengan mitos yang tanpa disadari justru melanggengkan subordinasi dan domestifikasi terhadap perempuan.
Kelemahan utama dari zine ini pada akhirnya memunculkan kesadaran akan pentingnya abstraksi teoritis atas fenomena sosial. Terlebih lagi zine ini mengambil tema pembahasan terkait alam dan perempuan yang notabene memerlukan kehati-hatian penuh demi menghindari kontradiksi paradigmatik. Kontradiksi yang saya maksud di sini ialah kecenderungan untuk memajukan agenda perempuan dalam wacana pengelolaan alam, namun secara tidak langsung juga turut melanggengkan ketidakadilan yang dialami mereka dalam konteks masyarakat patriarki. Mengingat dualitas sikap inilah yang sangat ditentang oleh ekofeminisme sebagai wacana yang memandang perjuangan ekologis sebagai bagian yang integral dengan politik emansipasi perempuan.
Namun, meski memiliki kelemahan yang sangat mendasar, zine ini tetap memiliki nilai kelebihan tersendiri. Sebab zine ini memberikan gambaran kasar kepada pembaca terkait potret pengelolaan lingkungan di Kota Malang berikut implikasinya terhadap ketidakadilan yang dialami masyarakat secara umum dan lebih khususnya lagi, perempuan. Minimal pokok bahasan dalam zine mampu menjawab rasa penasaran saya perihal akar persoalan di balik banjir bandang yang melanda Kota Batu pada 2021 silam yang sejalan dengan pendapat para ahli. Selain itu zine ini juga membuka wawasan yang lebih luas tentang tata kelola air di Kota Malang yang sangat diperlukan sebagai bahan diskusi menyoal hubungan antara alam dan perempuan.