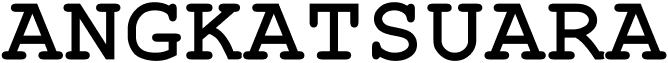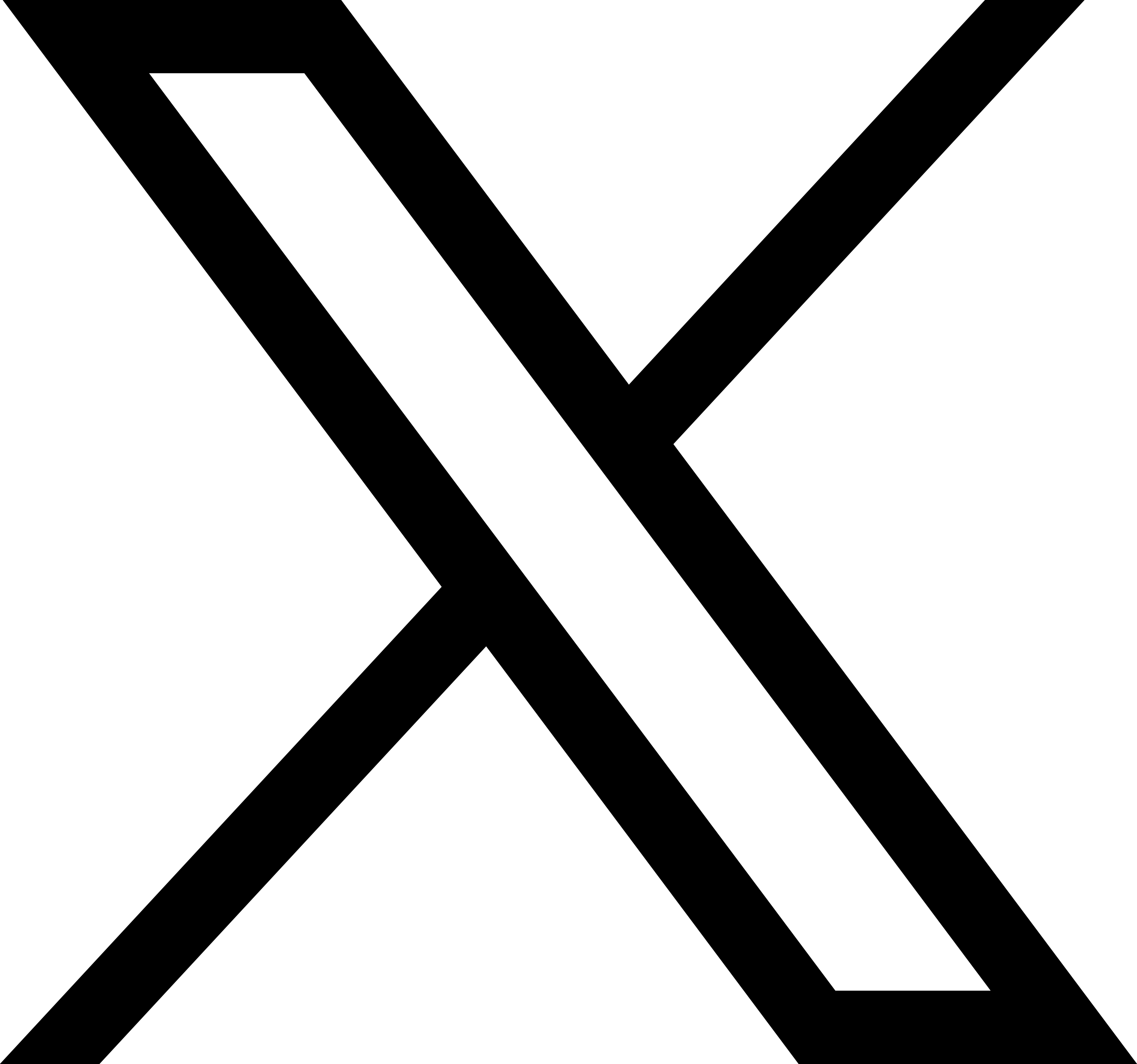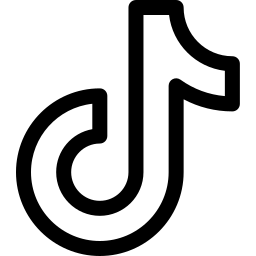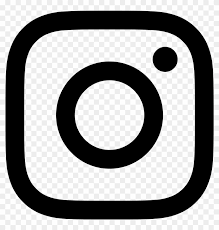Pemujaan perempuan dalam sejarah ternyata berasal dari fantasi penulis Belanda (yang kebanyakan laki-laki) terhadap perempuan pribumi. Laki-laki identik dengan kekuasaan, maka salah satu yang membuat mereka tertarik dengan pribumi adalah perempuan yang memiliki kebiasaan yang menyimpang dari tradisi (kepatuhan perempuan pada kuasa), seperti Cut Nyak Dien, Cut Mutia, Nyi Ageng Serang, Martha Christina Tiahahu. Selain itu, perempuan yang memiliki pemikiran dan kegiatan yang sejalan dengan misi politik etis juga menjadi ketertarikan tersendiri. Perempuan-perempuan itu diberikan kesempatan untuk mengenyam pendidikan (Kartini, Dewi Sartika, Maria Walanda Maramis). Dan mereka cenderung memilih perempuan dengan karakteristik yang sama. Perempuan yang memiliki trah kebangsawanan, dekat dengan kekuasaan, serta dicirikan menarik secara fisik dan kesamaan pemikiran dengan visi Belanda—seperti Kartini dan adik-adiknya.
Narasi di atas merupakan salah satu yang dapat saya tangkap dari tulisan Ruth Indiah Rahayu (2007) yang berjudul Konstruksi Historiografi Feminisme Indonesia dari Tutur Perempuan. Sialnya setelah membaca tulisan itu, saya justru menyadari bahwa saya mirip dengan penulis Belanda yang diceritakannya. Saya mengagumi perempuan yang berbeda dari yang lain, perempuan yang melawan dan memiliki pemikiran nyeleneh. Menemukan fakta ini membuat ego saya terkoyak dan cukup sakit hati. Mengapa? Karena ada satu sisi yang membuat saya merendahkan dan membenci mereka yang tidak cukup kompeten jika dibandingkan dengan saya. Di sisi lain juga membuat saya menyadari bahwa cara saya berpikir pun dibentuk oleh budaya laki-laki yang memungkinkan saya memiliki pandangan demikian.
Melalui tulisan itu pun, saya menyadari bahwa penulisan sejarah dari sudut pandang laki-laki ini amat berperan dalam menguatkan narasi persaingan antar perempuan, terutama secara personal. Hal ini tentu berpengaruh bagi setiap kehidupan perempuan, termasuk saya. Dalam kasus saya, bila menemukan perempuan yang memiliki pandangan berbeda dan dirasa lebih kompeten dari saya, sering kali membuat saya insecure dan terus membandingkan diri dengannya. Kondisi ini sangat menyakitkan ketika menyadari bahwa kami seharusnya bisa saling berkolaborasi dan membangun kekuatan. Upaya ini lantas terhambat oleh pikiran-pikiran saya yang serba kurang dan terus membandingkan diri dengan perempuan lain.
Idealnya kami dapat membangun kekuatan untuk membantu perempuan lain. Kami juga dapat saling menceritakan kisah-kisah kami. Dengan kisah yang semakin beragam, bukankah seharusnya akan membantu kami saling memahami dan membuka pandangan bahwa ada kisah lain yang perlu dihargai pula? Tapi, sepertinya patriaki tidak menghendaki itu. Maka dari itu, ia harus dilawan bukan?