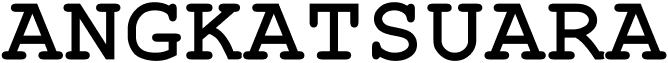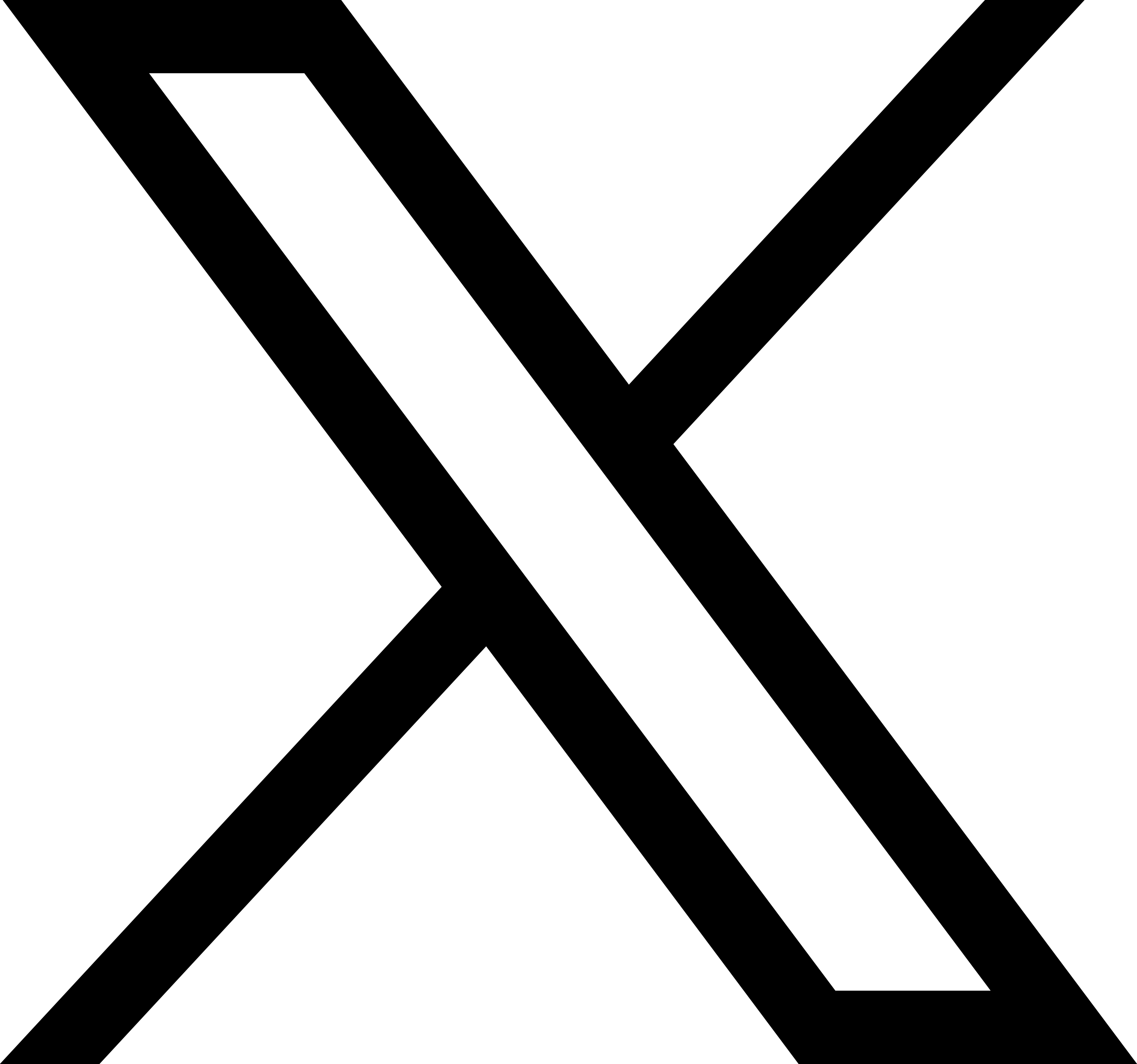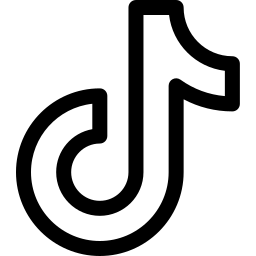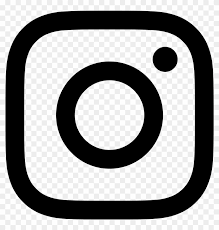Di tengah perjalanan pesta demokrasi 2024 mendatang, urgensi partisipasi perempuan sebagai peserta Pemilu menjadi isu yang sering mencuat. Pijakan argumentasinya pun demikian beragam. Ada yang mengulas dari perspektif hukum. Ada juga yang menggunakan kajian yang lebih radikal, seperti kajian feminisme marxis.
Gagasan tersebut tidak salah. Sebab mendorong meningkatnya partisipasi perempuan sebagai peserta Pemilu adalah hal yang memang semestinya dilakukan. Dengan cara itu, probabilitas angka perempuan di bangku kekuasaan kelak akan semakin meningkat. Hal ini akan menjadi salah satu corong membuminya prinsip “equality before the law”, yang menuntut “setiap orang” memiliki kedudukan dan kesempatan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan.
Meski demikian, diskursus perempuan dan kekuasaan tentunya tidak boleh hanya tersematkan pada persoalan jumlah perempuan di bangku pemerintahan. Tetapi juga harus diimbangi dengan terakomodirnya hak-hak dan perlindungan perempuan dalam substansi kebijakan publik yang dibentuk.
Berkaca pada sejarah, tidak sedikit kebijakan kekuasaan yang mengesampingkan hak-hak perempuan dan terlihat diskriminatif. Partisipasi perempuan dalam Musyawarah Pembangunan (Musrembang) dan kegiatan Reses legislatif hanya berada di level “tokenism participation.” Menurut Sherry R. Arnstein (1969), tokenism participation adalah model partisipasi semu/seremonial, di mana ruang aspirasi perempuan disediakan tetapi substansi dari aspirasi tersebut tidak diakomodir dalam kebijakan publik yang dibentuk. Problem inilah yang kemudian memicu lahirnya kebijakan publik yang tidak berpihak dan diskriminasi terhadap kaum perempuan.
Atas dasar itu, tuntutan peningkatan jumlah keterwakilan perempuan di bangku pemerintahan penting kiranya diikuti dengan gagasan terakomodirnya hak-hak dan perlindungan perempuan dalam substansi kebijakan publik yang dibuat. Tanpa hal tersebut, adalah sebuah keniscayaan bahwa kezaliman rezim terhadap perempuan akan terus berlanjut.
Problem Perempuan Dalam Kebijakan Publik
Secara historis, pemerintah memang telah melakukan beberapa upaya untuk menghapuskan diskriminasi terhadap perempuan. Di 1984, pemerintah meratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (Convention on The Elimination of all Forms Discrimination Against Women) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984. Kemudian pada 2000, pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Nasional.
Inpres PUG mulanya menjadi angin segar bagi kalangan perempuan. Sebab regulasi ini mendorong lahirnya kesempatan, pengakuan dan penghargaan yang sama terhadap perempuan dan laki-laki dalam kebijakan publik baik ditingkat pusat maupun daerah.
Meski demikian, hingga saat ini kemajuan yang dicapai masih sangat rendah. Komitmen pemerintah untuk benar-benar menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kebijakan publik belum mengalami kemajuan yang berarti. Bangunan argumentasi ini bukan tidak berdasar. Hal ini dapat dibuktikan lemahnya peran kebijakan negara dalam melindungi hak-hak perempuan di berbagai sektor.
Pertama, pada sektor pendidikan, data Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2016, menunjukkan bahwa rata-rata perempuan di Indonesia hanya berpendidikan sampai kelas tujuh (kelas dua) SMP (Kompas, 2023). Sejalan dengan hal tersebut, pada 2021, rata-rata lama sekolah untuk perempuan adalah 8,17 tahun, sementara laki-laki adalah 8,92 tahun. Perbedaan sebesar 0,75 ini tergolong signifikan karena perkembangan periode lama sekolah setiap tahunnya rata-rata sebesar 0,10 tahun saja (Andriana Lisnasari, 2023).
Kedua, di sektor ketenagakerjaan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan juga masih terbilang jauh di bawah laki-laki. Pada tahun 2018, TPAK perempuan hanya berada pada angka 51,88%, sedangkan laki-laki yang sudah mencapai 82,69% (Kompas, 2020). Selain itu, upah rata-rata per-jam untuk perempuan saat ini juga jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Di mana upah rata-rata per-jam untuk perempuan adalah sebesar Rp17.848,00, sedangkan laki-laki mencapai angka sebesar Rp18.210,00 (Andriana Lisnasari, 2023).
Selain catatan di atas, lemahnya keberpihakan dan diskriminasi negara terhadap perempuan dijustifikasi oleh Komnas Perempuan, yang mencatat bahwa pada 2022 sedikitnya terdapat 20 kebijakan negara yang memuat diskriminasi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap perempuan (Komnas Perempuan, 2023).
Melihat langgengnya kebijakan negara yang diskriminasi terhadap perempuan tersebut, penulis kemudian bertanya, ihwal apa yang menyebabkan hal demikian terus terjadi? Dari beragam jawaban yang digagas, jawaban yang paling menarik datang dari seorang kawan yang mengatakan bahwa “Langgengnya diskriminasi tersebut disebabkan oleh masih mengakarnya budaya dan ideologi patriarki di dalam masyarakat maupun di ruang-ruang birokrat (pemerintahan). Akibatnya, kebijakan negara yang diskriminasi terhadap perempuan tersebut terus berlanjut dan terlegitimasi, bahkan eksistensinya terkesan dibiarkan.”
Sumber Gambar: Freepik.com