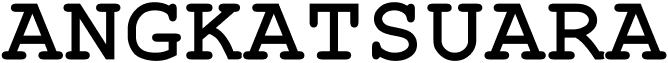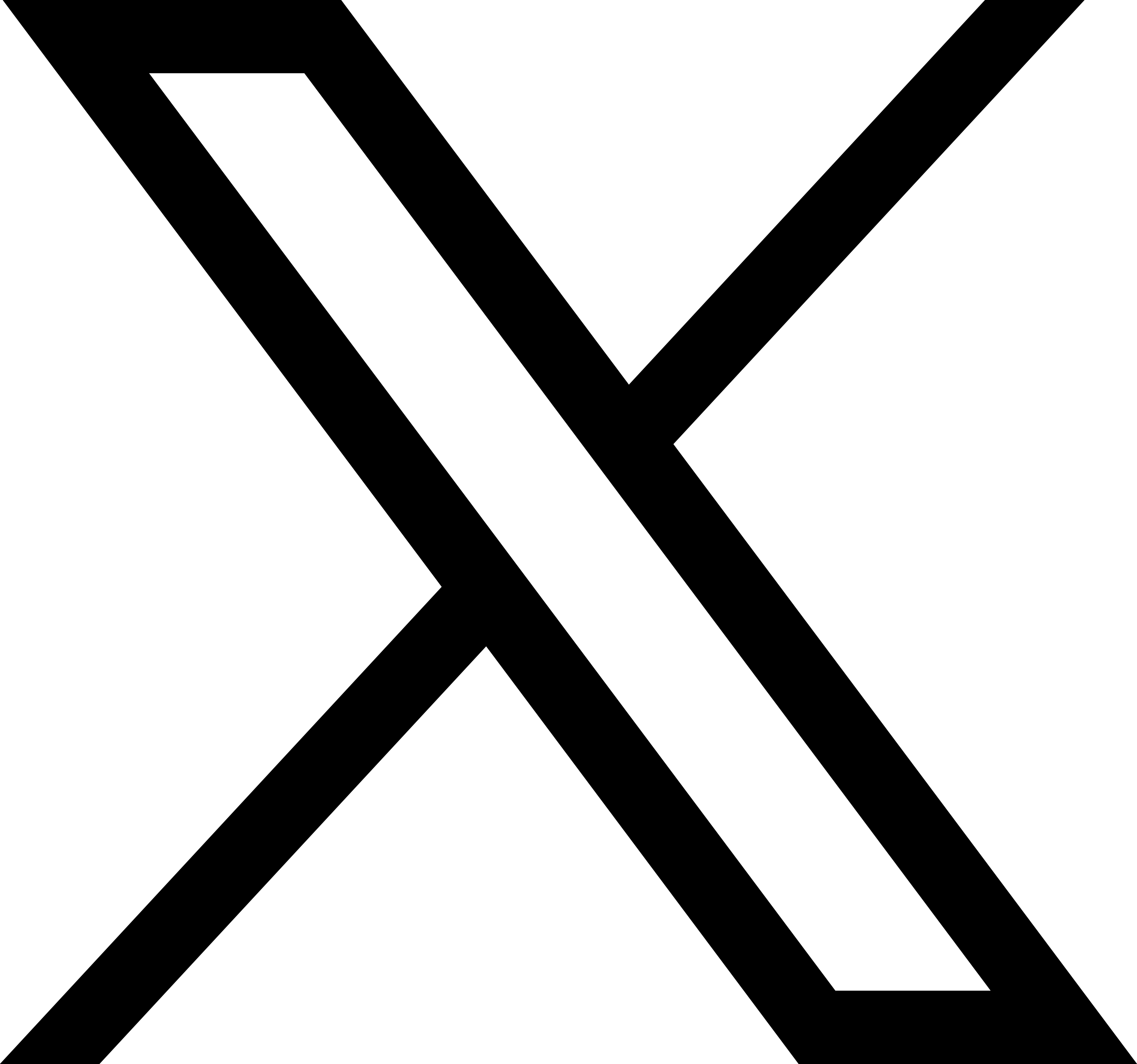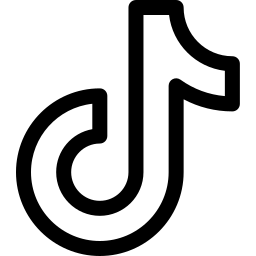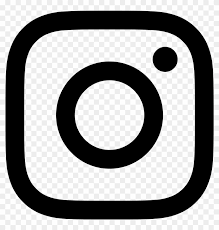Kasus pelecehan seksual marak kita temukan di kehidupan, baik di media sosial, ruang publik, sekolah, maupun ruang alternatif yang dibangun salah satunya atas dasar kesetaraan gender. Kasus pelecehan tersebut dapat berbentuk dan dilakukan secara non-verbal maupun verbal. Tentunya, ini menjadi topik pembahasan yang banyak dimuat dalam konten edukatif di media sosial. Tak hanya itu, di dalam Skena, persoalan pelecehan seksual juga kerap kali disuarakan oleh organizer, kolektif, band, ataupun individu-individu yang peduli. Slogan no place for sexism sudah tidak asing dilihat, dibaca, dan didengar di dalam lingkaran tersebut. Bahkan, dalam beberapa gigs, terdapat MC yang dengan tegas mewartakan hal tersebut dengan kemasannya masing-masing. Harapannya, dengan melakukan itu, orang-orang akan lebih peduli dengan batasan yang harus dijaga. Dengan demikian, gigs dapat berjalan dengan kondusif, menyenangkan, dan tidak menjadi pengalaman traumatis bagi siapapun.
Namun, bentuk upaya dari beberapa MC tersebut ternyata masih belum cukup efektif. Nyatanya, kita kerap kali menemui atau bahkan mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan itu. Bahkan, terkadang seseorang tidak sadar bahwa ia sedang dilecehkan. Mungkin sebagian orang memahami pelecehan hanya sebatas dipegang atau kontak fisik pada area intim saja. Padahal, pelecehan seksual sering terjadi secara verbal—nahasnya, masalah ini terkadang diabaikan, atau mirisnya malah dianggap sebagai pujian. Catcalling, lelucon, dan komentar tubuh yang merujuk pada hal seksual atas tubuh seseorang, objektifikasi, maupun pertanyaan mengenai aktivitas seksual juga termasuk dalam pelecehan seksual.
Kita mungkin sering berpapasan dan berdiskusi secara personal dengan orang yang ternyata memiliki awareness yang cukup tinggi terkait pelecehan seksual. Namun, tidak semuanya memiliki cukup energi untuk menulis, memuatnya dalam lirik lagu, mengajak banyak orang untuk melakukan hal yang sama, atau melakukan hal-hal lain dengan tujuan yang serupa. Tidak ada yang salah dengan itu, sebab aku akui memang perlu energi yang cukup banyak untuk melakukan hal tersebut. Belum lagi, tanggapan publik terkait upaya penyadaran masalah pelecehan belum tentu menyenangkan. Bisa jadi, kamu akan mendapatkan cap sebagai bagian dari kelompok tertentu, dianggap tidak asik, atau malah jadi bahan bercandaan. Aku paham bahwa setiap hal pasti menuai pro dan kontra—namun, apakah logis jika kontra pada upaya penyebaran awareness terkait pelecehan seksual yang dapat menimpa siapa pun, kapan pun, dan di mana pun?
Sering kali, kita mendengar lelucon yang merujuk pada hal-hal seksual. Aku tahu, pasti tidak akan nyaman jika kita terjebak di sana. Namun, ketika kita berusaha untuk menghentikannya, bisa jadi kita diolok-olok dengan sebutan “mudah baper”, atau mereka malah menunjukkan sikap defensif dan mengatakan bahwa itu hanyalah sekadar lelucon. Belum lagi, jika yang dijadikan lelucon adalah diri kita. Di situasi tersebut, sebenarnya kita berhak untuk marah dan pergi meninggalkan mereka. Namun, jika kamu memiliki energi yang cukup, cobalah berbalik “menyerang” mereka. “Serangan” itu dimaksudkan untuk menyadarkan mereka bahwa perilaku tersebut tidak dapat ditolerir dengan alasan apapun. Mari kita buat perumpamaan sederhana. Jika kekasih, adik atau kakak perempuan, ibu, ataupun orang-orang terdekat mereka dijadikan lelucon yang bersifat melecehkan secara seksual, apakah mereka terima?
Cerita mengenai pelecehan seksual sering kali hanya berputar di kawan-kawan yang dipercaya dapat menerima dan menyimpan hal itu saja. Ada penyintas, atau mungkin banyak penyintas yang memutuskan untuk tidak melakukan speak up pada pihak panitia atau pernyataan secara pribadi melalui media sosial terkait peristiwa tersebut. Tentunya, hal ini terjadi bukan tanpa alasan. Maskulinitas yang mendominasi membuat kawan-kawan perempuan ragu untuk menyuarakan apa yang telah mereka alami. Belum lagi, takut akan dibilang hanya mencari atensi, atau bahkan dianggap bahwa merekalah yang menggunakan pakaian yang mengundang nafsu laki-laki. Padahal, tentu saja tidak ada orang yang rela membeli tiket hanya untuk digerayangi tubuhnya, dijadikan objek, atau dilecehkan.
Peristiwa itu pun pernah kualami. Dilecehkan oleh orang yang selalu menggaungkan kesetaraan tentunya amat traumatis dan mengecewakan. Aku sempat berpikir bahwa semua obrolan tentang kesetaraan hanyalah bualan, tidak ada ruang yang benar-benar aman dan setara. Omong kosong soal kesetaraan ini diperkuat dengan tidak adanya langkah atau tindakan yang diberlakukan dari lingkup tersebut kepada pelaku untuk memberikan efek jera. Semuanya malah berbalik menyerang padaku. Saat itu, aku benar-benar muak, kecewa, dan merasa sendirian. Namun, aku terus berusaha melawan traumaku sembari mencari referensi bacaan dan mengoreksi diriku. Aku juga mulai mencari “tempat” yang menurutku lebih aman.
Aku amat senang ketika aku bisa kembali. Di tempat baru ini, aku bertemu dengan banyak kepala yang aware akan seksisme. Namun tetap saja, mengorganisir individu bukanlah suatu hal yang mudah. Aku kembali mendapatkan pelecehan seksual di tengah-tengah gigs yang masih berlangsung. Hal itu juga yang memantik diriku untuk membuat tulisan yang dimuat di salah satu media kawan-kawan. Selain sebagai bentuk speak up, aku juga berharap tulisan tersebut dapat sampai ke penyintas lain untuk saling menguatkan, syukur-syukur mereka bisa terpantik. Tak hanya itu, aku juga berharap tulisan tersebut dapat menjadi evaluasi baik secara individu maupun kelompok agar tidak ada lagi pelecehan seksual yang terjadi, baik di lingkup skena maupun umum.
Menurutku, tidak cukup diselesaikan dengan tulisan atau ujaran saling jaga satu sama lain, sebab semestinya tiap orang memahami batasannya masing-masing. Hal ini tentunya bukan tanggung jawab organizer, kolektif, ataupun band. Namun, jika mereka memilih untuk membantu menyuarakan hal tersebut tentunya adalah hal yang amat baik. Di luar hal itu, menjadi individu yang memahami batas dan tidak melecehkan siapapun adalah hal dasar yang harus dimiliki. Jika hal tersebut belum terpenuhi, menurutku jangan berinteraksi dengan manusia lain, sebab tidak perlu menunggu menjadi anggota atau bagian dari suatu kelompok tertentu, atau menganut isme-isme tertentu untuk tidak melakukan pelecehan seksual.
Maskulinitas dan dominasi laki-laki inilah yang membuat kawan-kawan perempuan melipir dan mencari ruang alternatif yang aman, dan mereka memilih Skena, berharap menemukan jawabannya. Berbicara soal skena, sebetulnya lingkaran ini amat luas. Namun, dalam konteks ini aku tekankan pada skena Hardcore Punk—sebuah wadah yang lahir dengan mengusung konsep kesetaraan. Bersamaan dengan itu, sudah seharusnya kesetaraan gender diterapkan pada banyak aspek. Contohnya, dengan melibatkan perempuan dalam suatu kegiatan (tidak hanya laki-laki yang menjadi panitia), memberikan ruang yang sama untuk perempuan, serta tidak melekatkan suatu hal buruk kepada perempuan, dan tentunya tidak melecehkan perempuan.
Skena yang menjadi pilihan alternatif ramah gender terkadang tercoreng, sebab masih saja ada peristiwa pelecehan seksual yang kebanyakan dialami oleh perempuan. Objektifikasi berupa tepuk tangan, lelucon yang bersifat merendahkan saat perempuan ada di moshpit, sorotan yang berlebihan, ditarik keluar dari moshpit, bahkan dianggap hanya mencari perhatian laki-laki saat ada di gigs maupun di moshpit. Tak hanya itu, pelecehan seksual dalam bentuk tindakan juga masih terjadi, mayoritas yang terjadi adalah diraba pada area intim. Ada yang mampu melawannya saat itu juga, namun ada juga yang memilih untuk diam saja—keduanya pasti sama-sama mengalami trauma.
Selain menghadapi pelecehan seksual, perempuan sering kali mendapatkan objektifikasi dari laki-laki. Mana yang lebih mending? Tentu saja tidak keduanya. Tidak ada yang lebih baik di antara keduanya. Bentuk objektifikasi yang kerap kali terjadi adalah sorotan kamera berlebih saat perempuan ada di moshpit. Hal itu biasanya juga diiringi dengan tepuk tangan, sorakan, bahkan siulan. Tak jarang, ketika perempuan tersebut merasa cukup dan memutuskan untuk keluar dari moshpit, ia akan mendapatkan pertanyaan seperti “tutor two step dong, kak”, “tutor moshing dong, kak”. Padahal, aktivitas tersebut seharusnya menjadi sesuatu yang wajar, sama seperti yang dilakukan oleh laki-laki. Namun, mengapa seolah-olah hal tersebut adalah hal yang amat luar biasa jika dilakukan oleh perempuan?
Belum lagi, anggapan bahwa seharusnya perempuan tidak perlu masuk ke moshpit. Mungkin, mereka mengemasnya dengan kalimat yang terdengar baik dan bijak, seperti “kamu nggak perlu moshing, nanti kamu kesakitan” atau “lebih baik kamu di belakang aja, supaya kamu aman”. Tentunya, kalimat itu menunjukkan dominasi laki-laki, membatasi ruang gerak perempuan, menganggap bahwa perempuan lebih rendah, dan menjadikan seolah-olah perempuan tidak punya otoritas atas dirinya. Mungkin bagi beberapa orang, kalimat yang bergaris bawah adalah hal yang berlebihan. “Cuma bilang nggak usah moshing aja kok jawabannya seperti itu” tapi memang begitulah sebenarnya.
Bahkan, ternyata pemikiran dan perkataan seperti itu masih belum cukup. Masih ada yang sengaja mencederai perempuan di moshpit hanya karena alasan bahwa dia adalah perempuan; tidak pantas, tidak layak, dan harus disingkirkan dari moshpit. Ya, tentu saja aku sepakat bahwa ketika kita berada di dalam moshpit, kita mengalami kekerasan atau cedera secara konsensual. Namun, jika tindakan tersebut dilakukan atas dasar tidak ingin ada perempuan di dalamnya, apakah itu tindakan yang dibenarkan? Bukankah hal demikian termasuk machois dan usaha untuk mengusir perempuan dari ruang yang seharusnya juga miliknya? Bukankah itu artinya juga merebut kesenangan orang lain? Aku tidak mengerti mengapa laki-laki bisa bertindak sedemikian rupa—hanya karena melihat perempuan ada di dalam moshpit. Apakah yang dilakukan perempuan di moshpit mencederai maskulinitasnya yang rapuh sehingga mereka terlihat tidak gagah dan kalah saing? Entahlah. Aku tidak mengerti.
Padahal, perempuan hanya ingin memiliki ruang, hak, dan kesempatan yang sama dengan laki-laki. Sebab apalagi tujuan perempuan bermigrasi ke ruang altrernatif (yang juga disebut skena) jika bukan karena adanya ruang setara? Sudah cukup stigma buruk publik yang melekat pada perempuan—yang mendengarkan, menghadiri, dan ada di tengah hiru pikuk musik cadas. Mengapa kita masih harus dibebankan untuk melawan dominasi dan merebut ruang yang seharusnya milik kita? Mengapa kesetaraan hanya mejadi sebuah kata yang terus menerus digaungkan jika dalam moshpit saja kita mendapatkan penyekatan? Bahkan, ada penuturan dari kawan-kawan perempuan bahwa hingga saat ini mereka belum berani untuk menghadiri gigs sebab takut akan diobjektifikasi dan dilecehkan. Sungguh amat disayangkan.
Lalu, bagaimana cara agar dominasi machois ini berakhir? Menurutku, langkah pertama adalah membangun kesadaran laki-laki yang berlagak machois—hingga mereka mau mengakui bahwa selama ini mereka telah mendominasi perempuan. Setelah kesadaran itu terbentuk, maka kita akan lebih mudah untuk saling berbenah. Selain itu, kita bisa menyebarkan kesadaran ini dengan menulis zine, membuat konten edukatif, membuka ruang diskusi (tentunya dengan melibatkan perempuan), atau mungkin kawan-kawan yang memiliki band bisa lebih vokal dengan membuat lirik yang bertemakan awareness terkait pelecehan seksual. Siapa pun bisa terlibat dalam hal ini. Semakin banyak, semakin bagus. Mari kita bersama-sama membuat pekak telinga para machois itu.
Selain itu, kita perlu menciptakan rasa aman bagi penyintas. Setidaknya, ada ruang untuk bercerita bagi para penyintas tanpa takut dihakimi oleh siapapun (tentunya penyintas bercerita berdasar konsen dan tanpa paksaan). Kemudian, berikan pilihan pada penyintas. Mungkin, ada penyintas yang memiliki energi dan mampu melakukan konfrontasi pada pelaku secara langsung. Hadirlah sebagai bentuk mediasi antara penyintas dan pelaku. Jika kita ingin menulis peristiwa itu sebagai salah satu bentuk bantuan speak up penyintas, mintalah izin terlebih dahulu—apakah ia berkenan untuk hal tersebut. Kita juga bisa menanyakan update mengenai kondisi penyintas, baik secara langsung maupun melalui orang terdekatnya. Berikanlah dukungan secara moral pada penyintas. Jika perlu, dampingi mereka ke psikolog.
Ada hal menarik yang bisa kita buat atas hal ini. Bagaimana jika kawan-kawan perempuan membentuk kolektif baru yang bertujuan untuk merangkul para penyintas? Setidaknya, dengan membentuk kolektif baru—paling tidak kita bisa menunjukkan usaha kita dalam melawan dominasi laki-laki. Kita juga bisa saling dukung satu sama lain. Mungkin, selama ini masih ada penyintas yang segan jika bercerita secara langsung pada kolektif (yang mana lebih banyak laki-laki di dalamnya), kehadiran kolektif perempuan dapat mengatasi masalah tersebut.
Untuk pelaku, hal paling utama yang perlu dilakukan adalah mengakui perbuatan tersebut dan meminta maaf, tolong turunkan egomu. Akuilah bahwa perbuatanmu telah melanggar batasan orang lain secara tidak konsensual. Jika kamu masih merasa benar atas hal tersebut, cobalah berdialog dengan kawan yang memiliki kesadaran akan pelecehan seksual. Jangan menghakimi penyintas dengan pembelaan dirimu. Setelah itu, coba tanyakan pada penyintas kira-kira bagaimana cara penyelesaian yang mereka inginkan. Teruslah menanyakan kabar penyintas (bisa melalui perantara/pendamping). Selanjutnya, kamu bisa menanyakan batasan untuk berkomunikasi dengannya. Beberapa penyintas tidak ingin bertemu atau ada di ruang yang sama dengan pelaku sebab mereka masih mengalami trauma akan peristiwa tersebut. Dengan melakukan hal tersebut, kamu turut membantu memulihkan keadaan penyintas dan kamu tidak akan dianggap sebagai pengecut.
Menurutku, perlu adanya sanksi serius untuk pelaku. Selain agar pelaku kapok, hal ini juga bisa menjadi pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan pelecehan seksual. Misalnya, saat ada penyintas yang melaporkan bahwa ia telah mengalami pelecehan seksual saat gigs tengah berlangsung dan ia dapat mengidentifikasi pelaku, segeralah membantu mencari pelaku. Jika pelaku sudah ditemukan, keluarkan ia dari gigs saat itu juga. Namun, jika penyintas mampu mengidentifikasi namun baru melapor saat gigs berakhir, tetap terima laporan tersebut. Mungkin, pelaku masih “koncone arek-arek”. Atau, jika penyintas kesulitan mengidentifikasi pelaku, kita tetap harus memberikan ruang yang aman untuk dia bercerita.
Jika pelaku masih bagian dari pertemanan kita, kita harus tetap mengakuinya sebagai pelaku dan tetap berpihak pada penyintas. Bagi sebagian orang, mungkin ini menjadi hal yang sulit dengan alasan “mau bagaimanapun, dia teman baikku. Kami pernah bla bla bla bla”. Ya, ia adalah kawanmu, tetapi saat ini posisinya adalah pelaku pelecehan seksual. Kamu tidak dapat membenarkan perilaku tersebut. Jika kamu memiliki energi yang cukup, cobalah berdialog dengan pelaku dan sampaikan bahwa perilakunya salah. Ia akan menjadi hebat jika berani mengakui perbuatan tersebut (yang berani-berani aja hehehe).
Aku harap dengan menulis ini, kita dapat saling mengevaluasi, belajar, dan berdiskusi untuk membangun ruang yang aman. Sekaligus, barangkali ada kawan-kawan perempuan yang sepakat atas ideku untuk berkolektif guna merangkul penyintas? (hehe). Aku juga berharap tulisan ini mampu memantik penyintas yang mungkin sudah lama memendam semuanya sendirian untuk bercerita dan menyelesaikan semuanya bersama-sama.
Tidak lupa, usir jagoan moshpit!
Sumber gambar: pinterest.com